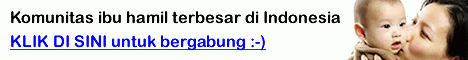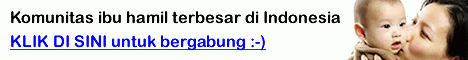Kantor kelurahan di suatu siang yang panas:
Petugas: “Pekerjaan Bapak?”, sambil mengisi formulir KTP dengan pinsil 2B.
“Bapak Rumah Tangga”, jawab yang ditanya kalem.
Petugas: “Maksudnya? Mana ada pekerjaan bapak rumah tangga?”, sambil keningnya berkerut.
“Ada, Pak. Ya saya ini.” Tersenyum lebar dengan mata berbinar.
“Emang kerjanya di mana dan tugasnya apa aja?” Tanya si petugas mulai gusar.
“Kerjanya di rumah, Pak. Bersihin rumah, nyuci baju, ngantar anak ke sekolah, belanja ke pasar, betulin mobil, pasang engsel pintu yang rusak, betulin koneksi internet, pokoknya tugasnya segudang, pak!” terangnya cepat dengan semangat ’45, seakan baru saja mencoba menjelaskan kegunaan alat pacu jantung pada penderita diabetes.
“Lha, emang ibunya ke mana? Udah cerai?” Tanya si petugas lagi masih bingung.
“Ibunya kerja lha, Pak! Nyari duit. Gantian saya yang di rumah, ngurusin semuanya, biar dia bisa konsen nyari yang banyak!” tukasnya sambil tetap tersenyum dengan wajah ramah.
“Berarti Bapak nganggur, kan? Kalau gitu, saya tulis aja di sini ‘tidak kerja’ ya, Pak? Soalnya tidak ada kolom ‘bapak rumah tangga’ di formulir ini, yang ada juga cuma ibu rumah tangga!” kata si petugas mulai tidak sabar.
“Lho, Pak? Gimana sih? Saya itu bukan pengangguran, Pak! Saya ini punya kerjaan, ya bapak rumah tangga itu! Masak dibilang pengangguran?!” Si bapak tidak tersenyum lagi. Berdiri, sambil mengusap keringat bayi mungil di gendongan sarung batik yang melilit badannya, dia berujar,”ya, sudah..! Bapak tulis aja di situ pekerjaan saya ‘wiraswasta’. Biar tidak bingung. Lagian saya emang lagi mau buka usaha ngajar bahasa Inggris di facebook kok!”, sahutnya membela diri sambil duduk kembali karena semua mata di ruangan itu tiba-tiba mengarah padanya.
***
Dialog di atas tentu saja hanya percakapan imajiner, terbetik setelah bincang santai di rumah teman saya hari Minggu kemarin. Bertiga dengan istrinya, kami bernostalgia tentang masa-masa kami kuliah dulu di negeri seberang. Waktu itu sebagian teman kami yang wanita membawa serta suami dan anak-anaknya. “Mumpung beasiswa kita mau nanggung,” begitu komentar mereka. Maka menjadi pemandangan umum lah setiap pagi di lingkungan tempat tinggal kami yang sebagian besar orang Indonesia, para bapak mengantar istri mereka berangkat kuliah, seminar atau field trip sambil menggendong anak mereka. Saat yang sama melihat bapak A menenteng belanjaan sambil mendorong kereta bayi atau pak B yang lagi berlari kesana kemari mengejar dua anak balitanya dengan sendok dan piring di tangan, berupaya membujuk mereka makan, sambil menunggu sang ibu pulang di sore hari. Para bapak teladan tersebut tentu saja bukanlah pengangguran di tanah air. Mereka punya pekerjaan tetap – pegawai Pemda di kota S, dosen perguruan tinggi swasta, pengusaha bengkel, arsitek, wartawan, dan lainnya. Di negeri tetangga pun mereka tidak sepenuhnya menganggur. Tiap sore dan malam hari atau akhir minggu mereka biasanya menjadi bagian dari ‘partai buruh’ atau pekerja kasar yang dibayar perjam. Ada yang jadi asisten koki, cleaning service, traffic surveyor, pengumpul telur di peternakan, dan lainnya.
Apa yang bapak-bapak tersebut lakukan juga bukanlah pengebirian hak lelaki sebagai kepala keluarga, atau pelecehan hak-hak prerogatif suami sebagai pencari nafkah yang telah lama disemai oleh budaya patriarkal kita dan dilegitimasi oleh aturan agama. Namun Ini adalah buah dari kesepakatan bersama mereka, antara suami dan istri, yang telah melalui proses musyawarah untuk bermufakat. Bahwa demi masa depan yang lebih baik, salah satu pihak harus berkorban dan mendukung pihak lainnya. Karena kesempatan tidak datang dua kali – kesempatan kuliah pascasarjana gratis, dan kesempatan bermukim di luar negeri sekeluarga. Ini tentu saja sesuatu yang langka bagi keluarga-keluarga tersebut. Tak heran pemandangan di atas terlihat begitu alamiah, kompak,rukun dan damai.
Hingga suatu hari, saat mereka pulang ke tanah air, dan kembali menyatu ke dalam keluarga besar dan berinteraksi dengan lingkungan lamanya…
Sebagaimana yang diceritakan oleh istri-istri mereka, Pak A dan pak B sebenarnya sudah merasa cocok dan mapan dengan “posisi” barunya yang bergelar manja, ‘housedaddy’ dan jabatan sebagai Kepala Urusan Rumah Tangga dan Perbendaharaan Keluarga. Di setiap kawinan, arisan dan takziah, sang istri pun selalu memujinya sebagai ‘suami dan ayah terbaik’. Anak-anak juga sudah terbiasa melihat housedaddy mereka ‘berprestasi’ di dapur dengan aneka olahan makanan dan minuman hasil praktek resep di blog dan facebook teman2nya.
Namun itu hanya berlangsung di tiga tahun pertama sejak mereka kembali ke tanah air. Dari bincang-bincang di hari Minggu itulah saya baru tahu kalau bapak-bapak teladan ini –sudah mulai merasa tidak nyaman dengan ‘pekerjaan’ mereka, terutama saat harus kongkow-kongkow dengan teman-teman lama atau hadir di reuni sekolah yang akhir-akhir ini marak diadakan. Mereka agak canggung jika harus terus terang tentang status mereka, sebagai yang dinafkahi dan bukan sebaliknya. Atau saat tahu bahwa sahabat karib mereka yang dulunya cuma jago nyontek dan biang bolos, sekarang sudah jadi wakil walikota ataupun pejabat publik lainnya. Sedang sebagian Bapak-bapak ini masih mampu untuk berprestasi ataupun mengaktualisasi kemampuan mereka seperti dulu. Hanya saja demi kesepakatan bersama, niat itu ditunda dulu. Memang seperti ada yang ‘hilang’ dari diri mereka. Belum lagi “hukuman” psikologis yang harus mereka terima saat harus menjelaskan peran dan posisi mereka ke keluarga besar dan masyarakat, yang umumnya belum bisa memahami dan menerima status baru ini.
Namun para suami ini juga sedang galau dan risau. Di satu sisi ingin kembali ke dunianya yang dulu tapi di sisi lain mereka harus menerima kenyataan bahwa saat ini istri-istri mereka memang saat ini lebih laju karirnya, dengan kesempatan yang lebih terbuka luas dibanding mereka. Istri pak A sedang mengejar gelar professor di bidang humaniora dan menjadi kepala pusat studi wanita di kampusnya. Istri pak B baru saja mendapat beasiswa untuk gelas PhD bidang sastra di negeri jiran, dan baru saja pulang dari perjalanan panjang untuk menampilkan karya drama sekuelnya di beberapa negara. Seakan tak mungkin bagi mereka untuk menahan laju karir dan merintangi kesempatan yang menjadi anugerah bagi pasangan mereka saat ini.
Akhirnya memang semua terpulang ke masing-masing pribadi karena kondisi psikologis, finansial dan kultural tiap keluarga tak ada yang sama. Tiap-tiap kita tentu saja punya standar yang berbeda untuk cara pandang, aturan rumah tangga, pola asuhan anak, mimpi untuk masa depan bersama dan lainnya, yang secara langsung maupun tidak, akan mempengaruhi keputusan suami dan istri untuk memilih, apakah ayah atau ibu yang diberikan kesempatan untuk melaju lebih cepat, menggapai mimpi-mimpi tersebut.
Atau malah… mengambil jalan tengah: dua-duanya saja. Setiap tiga hingga lima tahun, tergantung kapan rasa bosan dan tidak nyaman itu muncul, sang suami ataupun istri akan berganti peran dan bertukar posisi sebagai pemberi nafkah dan yang dinafkahi - sebagai pemegang kendali atas mimpi-mimpi dan hasrat yang terpendam untuk segera diaktualisasikan. Agar kedua pihak tetap bisa membuktikan kepada dunia bahwa dirinya masih ada dan masih ‘patut untuk diperhitungkan’. Apalagi pilihan untuk tinggal di rumah bukanlah putusan seumur hidup yang pantang untuk diubah. Semuanya memang tergantung pada pengertian dan kesepakatan berdua.
Jadi sahabat, mari katakan Yes to househusband and Yes to housewife!
sumber